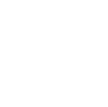Kotbah Jum'at
AGAMA DAN PANCASILA DALAM IDENTITAS KEINDONESIAAN*
M. Amin Abdullah
Abstrak
Publik melihat penomena yang sama sekali kontras antara pandangan dunia dan kehidupan sosial-politik-agama Muslim di wilayah Timur Tengah dan pandangan dunia dan kehidupan sosial-politik-agama Muslim di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alih kepemimpinan nasional di Indonesia dari order Baru ke orde Reformasi (1998) relatif lancar, tidak berlarut-larut, kemudian diikuti pelaksanaan Pemilu dan Pilpres (2004;2009) dan yang paling berjalan damai tanpa kekerasan tahun 2014. Adapun alih kepemimpinan sosial-politik-agama di negara-negara Timur Tengah (Arab Spring) selalu dibayang-bayangi dan diikuti dengan tindakan kekerasan sosial-politik-agama yang membawa banyak korban. Bahkan yang sekarang, ditengah krisis politik di Iraq dan Suria, memunculkan faksi Islam garis keras yang mendeklarasikan Islamic State of Iraq and Syuria (ISIS). Sebelumnya, krisis politik di Iraq dan Afganistan memunculkan al-Qaeda. Keduanya tidak hanya menimbulkan banyak korban sipil di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan dampak ke luar, membawa kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan internasional. Apa yang menyebabkan peralihan dan alih kepemimpinan di negara Indonesia relatif dapat berjalan lancar, sukses dan damai, tanpa menimbulkan korban yang berarti? Bagaimana hubungan antar agama dan Pancasila ? Bagaimana peran ulama, cendekiawan dan intelektual Muslim Indonesia di dalam mengawal konstitusi, demokrasi dalam negara-bangsa Indonesia modern? Peran apakah yang diemban oleh perguruan tinggi agama negeri dan swasta (PTKIN-PTKIS) dalam merawat demokrasi, kebinnekaan dan hak-hak kultural suku-suku dan penganut agama-agama dan kepercayaan yang menjadi pilar penting kehidupan berbangsa dan bernegara era Indonesia modern? Apa ancaman yang dihadapi sekarang di era global? Tulisan ini ingin merefresh apa sumbangan ulama, cerdik cendekia dan intelektual Muslim Indonesia melalui perkembangan pemikiran Islam Indonesia (agama) dalam merawat kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila) untuk kesejahteraan warga dan perdamaian dunia.
Kontekstualisasi pemikiran Islam.
Memperbincangkan Pemikiran Islam, menurut hemat saya, tidak bisa tidak, memang harus melibatkan konteks, yaitu konteks kultural, konteks sosial bahkan juga konteks perkembangan sains. Pemikiran Islam dimanapun selalu terjalin kuat, lengket dengan kondisi tempat dimana pemikiran Islam itu dipahami, tumbuh, menyebar dan berkembang dan tidak kalah pentingnya adalah tingkat perkembangan ilmu pengetahuan. Pemikiran Islam tidak dapat lepas dan keluar jauh dari konteks ruang dan waktu (space and time; al-zaman wa al-makan [zamkany] dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan (nadzariyyatu al-ma’rifah) dimana ia dipahami, dikaji, tumbuh dan berkembang.[1] Ketika pemikiran Islam tumbuh dan berkembang di wilayah Timur Tengah akan sangat berbeda corak rancang bangun epistemologi, wajah dan tampilan sosio-kulturalnya ketika ia tumbuh dan berkembang di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara. Begitu pula ketika ia sekarang mulai bersemi dan nantinya akan tumbuh dan berkembang di wilayah Barat seperti Eropa, Amerika, Australia dan begitu seterusnya yang pada saatnya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari intellectual discourse umat Islam dimanapun berada..[2] Belum lagi jika kita bicara bagaimana proses dan tumbuh perkembangannya di wilayah Afrika yang begitu luas sejak dari Afrika Utara, Tengah sampai Afrika Selatan. Singkatnya, rupanya berbeda benar corak perkembangan dan tampilan sosial-kultural dan politik agama yang tumbuh dan berkembang di wilayah benua-darat (continental) dan yang tumbuh dan berkembang di dunia kepulauan (archipelago). [3]
Bagaimana memahami perkembangan pemikiran agama, dalam hal ini adalah pemikiran Islam, di berbagai daerah dan wilayah di dunia yang sangat berbeda-beda sesuai dengan konteks masing-masing tersebut?[4] Tidak mudah memahaminya jika kita hanya menggunakan corak pendekatan lama, pendekatan tekstual-teologis. Jalan yang ditempuh tidak ada jalan lain, kecuali kita harus berani keluar dari format teologi-tekstual ke format teologi-kontekstual. Dalam hal mengkaji dan mencermati teologi-kontekstual, diperlukan masukan dan sumbangan dari cara pandang keilmuan lain seperti ilmu-ilmu sosial dan humaniora[5]. Sekedar sebagai contoh, cara melihat dan membaca peradaban Islam oleh seorang sejarawan Marshall G. S. Hodgson dalam bukunya The Venture of Islam[6], akan dapat membantu melihat bagaimana peradaban Islam berkembang dalam lintasan sejarah yang panjang dan sekaligus dapat juga digunakan untuk membaca bagaimana jaringan ulama, intelektual dan para sarjana Muslim berupaya mengembangkan pemikiran Islam Indonesia, termasuk Indonesia modern era negara-bangsa saat sekarang ini.
Marshall Hodgson membedakan tiga bentuk fenomena peradaban Islam, yaitu pertama, penomena Islam sebagai doktrin (Islamics), kedua, fenomena ketika doktrin itu masuk dan berproses dalam sebuah masyarakat-kultural (Islamicate) dan mewujudkan diri dalam konteks sosial dan kesejarahan tertentu. Dan ketiga, ketika Islam menjadi sebuah fenomena “dunia Islam” yang bersifat politis dalam lembaga-lembaga kenegaraan (Islamdom) yang bertolak dari konsep “dar Islam”, sebagaimana pula yang terjadi di dunia Kristen, Christendom, dimana ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur’an atau Injil berlaku. Dengan begitu, ada 3 kata kunci penting untuk memahami sejarah dan peradaban Islam di pentas dunia, yaitu Islamics, Islamicate dan Islamdom[7].
Pada level akademik di perguruan tinggi, para akademisi di lingkungan perguruan tinggi agama Islam pada tahun 80 an mulai membaca dan mengenal buku-buku sejarah (peradaban) Islam dan sosiologi agama. Tidak hanya literatur kitab kuning (Nahw, Sorf, Fikih, Kalam, Tafsir, Hadis) seperti yang biasa mereka kenal sebelumnya, khususnya di lingkungan dunia pesantren, baik salaf maupun khalaf. Yang saya maksud disini para dosen dan mahasiswa membaca sejarah (peradaban) Islam tidak hanya dari perspektif orang dalam (insider), tetapi juga membaca sejarah (peradaban) Islam dari perspektif orang luar (outsider), yakni membaca sejarah Islam dalam konteks sejarah perkembangan agama-agama dan peradaban dunia. Buku Marshall G. S. Hodgson menjadi salah satu buku rujukan, disamping yang lain-lain, yang pada saatnya akan sangat membentuk pola pikir keagamaan dan keislaman yang berbeda dari corak pemikiran Islam dari para kolega baik di Indonesia maupun di Timur Tengah.
Salah satu ciri pokok pemikiran Islam Indonesia yang hendak dikembangkan di perguruan tinggi Islam [sekarang disebut Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta (PTKIN/S] adalah adanya sense, keharusan melibatkan analisis ilmu-ilmu sosial dalam memahami realitas dan dinamika pemikiran Islam. Ia tidak lagi hanya terjebak, puas dan berhenti pada pemikiran Islam klasik, atau yang populer sekarang disebut dengan Turath (disini, saya memahaminya dalam makna yang sangat terbatas, yaitu Islam dalam Text dan atau nash semata). Ia telah mampu menembus dan melihat peradaban Islam dalam realitas lintasan sejarah sosial-budaya konkrit yang mengitari dan mengelilingi text dan atau nash baik era klasik, tengah maupun modern ( al-nash wa ma haulahu). Generasi tahun 80 an menyebutnya dengan Kemoderenan (al-Hadatsah). Pergumulan sosial-intelektual itulah yang kemudian ditukikkan ke dalam alam pikiran Muslim Indonesia (Islam dalam Context). Keduanya kemudian dirajut sedemikian rupa dalam buku-buku seperti antara lain bukunya Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin dan Peradaban[8].
Sejak awal munculnya generasi intelektual baru dalam pentas diskursus pemikiran Islam di Indonesia, ide-ide Kalam dan Aqidahnya Ibn Taimiyyah, tasawwufnya al-Ghazali dan Ibn Araby, fikihnya Ibn Rusdh dan para pemikir Muslim klasik yang lain, telah tergambar dengan jelas dalam buku Khazanah Intelektual Islam[9]. Semuanya itu kemudian didialogkan dan dikawinkan dengan pemikiran sejarawan, seperti Marshall Hodgson, sosiolog agama, seperti Robert N. Bellah dan lain-lain, yang kemudian menyatu dan diblender dalam pemikiran dan kerangka analisis yang utuh. Dalam tampilan generasi intelektual Muslim baru tahun 80 an ke depan di muka publik, dalam seminar, ceramah dan pidato, perkawinan dan jalinan antara khazanah intelektual Muslim klasik (al-Turath) dan ilmu-ilmu sosial modern (al-Hadatsah) selalu nampak disitu. Itulah salah satu ciri dari sekian ciri yang lain, yang membedakan antara generasi intelektual Muslim tahun 80 an dan lainnya dalam alam pikiran Keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan di Indonesia.
al-Hanifa al-samha’[10], diversitas, inklusivitas dan multikulturalitas.
Bagai petir yang menyambar di siang bolong ketika Nurcholish Madjid dan kawan-kawan dengan lantang dan firm bicara tentang pemikiran Islam yang bercorak al-hanifa al-samha (toleran, kelapangan, open, terbuka), pluralitas (al-ta’addudiyyah) dan inklusivitas (al-tadhamuniyyah), dan sekarang secara akademik lebih dikenal dengan multikulturalitas (ta’addud al-tsaqafaat/al-hadharaat wa al-diyanaat). Menyambar di siang bolong karena umumnya pemikiran Islam yang berkembang di pesantren-pesantren, perguruan tinggi Islam, apalagi perguruan tinggi umum, belum lagi menyebut berbagai jenis ceramah-ceramah keagamaan Islam di majelis-majelis taklim, halaqah-halaqah dan daurah-daurah Tarbiyah, dan juga yang dikembangkan di berbagai organisasi keagamaan Islam di tanah air pada saat itu tidak lah seperti itu coraknya. Umumnya masih bercorak eksklusif, tertutup, sektarianistik, primordialistik, parokialistik, madzhabiyyah, hizbiyyah, ta’ifiyyah. Situasi dan psikologi sosial-politik keagamaan di tanah air saat itu – bahkan sampai batas tertentu sampai sekarang dan sampai kapanpun – masih ada tersimpan keinginan dari sebagian warga dan kelompok yang ingin menghidupkan kembali adanya semacam Islamdom (Islam politik, sistem khilafah, al-daulah al-Islamiyyah) karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (87%). Wajar jika ada beberapa kelompok berkepentingan yang menginginkan berdirinya semacam negara agama atau negara Islam disini, namun sayangnya dengan menepikan, mengesampingkan dan melupakan kesepakatan founding fathers, ijtihad politik para pendiri republik, negara-bangsa, Indonesia tahun 1945.
Diktum yang diproklamirkan Nurcholish Madjid adalah “Islam yes, partai Islam, No ?”. Yaitu, Islam yang bercorak al-hanifah al-samha’, yang toleran, terbuka, yang dapat menerima dan bekerjasama dengan orang dan kelompok lain dalam membangun Indonesia yang majemuk dan mensejahterakan warganya secara bersama-sama adalah Yes. Bukan Islam yang bercorak sektarianistik, primordialistik, mazhabiyyah, hizbiyyah dan ta’ifiyyah, yang tidak dapat menerima, apalagi bekerjasama dengan orang, organisasi dan kelompok, agama, suku, ras lain yang berbeda. Meskipun pahit dirasakan saat itu, namun dapat dirasakan manisnya saat sekarang ini, khususnya ketika kita semua, sebagai keluarga besar dan warga bangsa Indonesia menikmati keindonesiaan kita bersama masa kini, khususnya dalam perbandingannya dengan melihat, mencermati dan mengikuti perkembangan sosial-politik-agama di wilayah Timur Tengah (Arab Spring).
Kegagalan merawat dan memperkuat sendi-sendi kehidupan dan tata kelola negara-bangsa di sebagian negara di Timur Tengah dan bagian dunia Muslim yang lain lantaran masih kuatnya ideologi, doktrin, pemahaman sosial-politik atau prinsip keislaman, yang tertutup, yang eksklusif, yang dikenal dengan sebutan al-walla’ wa al-barra’[11] (setia dan loyal hanya kepada orang, golongan, kelompok, organisasi, sekte, partai yang seagama, sekeyakinan, semadzhab, sehaluan atau segolongan sendiri dan tidak setia, tidak loyal atau menolak adanya pemimpin yang tidak berasal dari golongan agama, madzhab, organisasi atau sektenya sendiri). Doktrin ini cukup ampuh ditanamkan oleh kelompok sosial politik yang saling bertikai memperebutkan kekuasaan sosial-politik di wilayah Timur Tengah dan di berbagai belahan dunia Muslim yang lain. Pertikaian antara golongan Sunni dan Syi’iy yang tidak kunjung selesai, bahkan semakin menjadi-jadi, di berbagai wilayah di Timur Tengah, termasuk merambah ke Asia Selatan, di Pakistan, berakar dari doktrin fiqh al-siyasah yang bercorak seperti itu. Ideologi takfir atau takfiriyyah yang tersebar di masyarakat dan di sosial media, yaitu meng-kafir-kan orang atau kelompok yang berpaham berbeda dari kelompok dan golongannya sendiri juga bersumber dari doktrin al-walla’ wa al-barra’ ini.
Dalam ideologi dan praktik sosial-politik-keislaman yang dideklarasikan oleh para pendiri Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), yang mengangkat isu dan mendeklarasikan secara sepihak apa yang mereka sebut sebagai al-khilafah al-Islamiyyah, sebagai antitesis atau antidote dari sistem pemerintahan republik yang demokrasi dan berkonstitusi yang dianggap gagal[12] di Iraq dan Suria, sangat jelas corak doktrin al-walla’ wa al-barra’ (loyalty and disavowal) tersebut. Bahkan doktrin loyalty and disavowal ini tidak hanya terbatas pada pemilihan kepemimpinan, tetapi juga melebar ke wilayah sejarah dan budaya. Penghancuran tempat-tempat ibadah milik pemeluk agama lain, penghancuran situs-situs budaya dan agama, seperti candi[13], patung-patung dan benda-benda bersejarah yang lain, yang dianggap sebagai simbol syirk, yang dianggap bertentangan dengan pemahaman subjektif aqidah dan syari’ah Islam yang mereka pahami[14]. Puncaknya adalah menggumpalnya dan hidup suburnya sektarianisme, parochialisme, primordialisme atau mazhabiyyah, hizbiyyah dan ta’ifiyyah di lingkungan umat beragama Islam yang melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial-kemasyarakatan dan sosial-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Puncaknya adalah munculnya apa yang dikenal sekarang sebagai tindakan kekerasan atas nama agama (violence; ‘unfiyyah), radikalisme, dan terrorisme (irhabiyyah).[15]
Inilah kekurangan dan kelemahan pemikiran Islam di Timur Tengah khususnya dan negara-negara Muslim pada umumnya, yang ditengarai oleh Ibrahim M. Abu Rabi’ sebagai pemikiran Islam yang tidak mengenal dan kering sentuhan social sciences dan masukan berharga dari pemikiran kritis-filosofis-akademis yang biasa dikaji dalam humanities kontemporer. Saya kutip pandangan Ibrahim M. Abu Rabi’:
“The core of the field revolves around Shari’ah and Fiqh studies that have been, very often, emptied of any critical or political content, or relevance to the present situation. A clear-cut distinction has been made between the “theological” and the “political” or the “theological” and the “social,” with the former being understood as rites, symbols, and historical text only. Furthermore, the perspective of social sciences or critical philosdophy is regrettably absent. The field of modern Shari’ah studies in the Muslim world has remained closed off to the most advanced human contributions in critical philosohy and social science”[16].
Terjemahan bebasnya sebagai berikut. Seringkali, sejak dari dahulu hingga sekarang, inti ruang lingkup bidang studi yang mengelilingi Syari’ah dan Fikih dikosongkan atau dijauhkan dari permasalahan politik dan studi kritis yang relevan untuk masa sekarang ini. Dibuat tarik garis batas pemisah yang tegas antara apa yang disebut “teologis” dan “politis” atau antara “teologis” dan “sosial”, dengan pemahaman bahwa yang pertama adalah semata-mata hanya terkait dengan ritus-ritus peribadatan, simbol-simbol, dan teks-teks sejarah saja. Lebih dari itu, sangat disesalkan bahwa perspektif ilmu-ilmu sosial atau filsafat kritis sama sekali tidak ada disitu. Biang kajian studi Syari’ah modern dalam dunia Muslim masih tetap tertutup untuk menerima masukan dari sumbangan pemikiran yang paling maju dalam filsafat kritis dan ilmu sosial.
Ide-ide besar H.A. Mukti Ali (Kerukunan umat beragama), Prof. Harun Nasution (Islam Rasional), Nurcholish Madjid (Sosiologi Agama), Ahmad Syafi’i Ma’arif (Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara) dan Abdurrahman Wachid (Pribumisasi Islam) yang ditulis dalam buku-bukunya kemudian disemaikan, ditangkap dan disebarluaskan baik langsung maupun tidak langsung oleh jaringan perguruan tinggi agama Islam di tanah air, temasuk perguruan tinggi di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah dan dalam batas tertentu dalam naungan Nahdhatul Ulama pada saat itu. Banyak jaringan lain yang berpartisipasi dalam merawat dan mengembangkan ide dan gagasan inklusivitas, kebinneka tunggal ikaan, keindonesiaan, al-hanifah al-samha’, namun yang melakukannya secara sistemik, akademik dan terstruktur adalah melalui jaringan Perguruan Tinggi Agama di tanah air. Gagasan pembaharuan pemikiran Islam tersebut, masuk core kurikulum dan silabi dosen mengajar dan memberi perkuliahan agama di perguruan tinggi.
Belakangan, sekitar tahun 90an, dan lebih-lebih tahun 2000 an, ide dan gagasan itu lebih berkembang lagi dengan berdirinya pusat-pusat studi di dalam dan di luar perguruan tinggi agama, pelatihan-pelatihan dan training-training yang diselenggarakan oleh masyarakat. Temanya pun berkembang menjadi lebih luas, seperti dialog antar budaya, dialog antar umat beragama, dialog budaya dan agama, agama dan gender, agama dan hak asasi manusia, agama dan mitigasi bencana, agama dan lingkungan hidup, agama dan multikulturalitas, agama dan ilmu pengetahuan dan begitu seterusnya. Apa pengaruhnya ini semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ternyata pemahaman dan pemikiran keagamaan Islam model kontekstual ini besar sekali pengaruhnya dalam proses panjang berkesinambungan, tanpa kenal lelah, nation building dan lebih-lebih character building.
Pengaruh dan impaknya hanya dapat dirasakan ketika masyarakat membandingkan kehidupan berbangsa dan bernegara manusia Muslim Indonesia dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai kawasan dunia yang lain, lebih-lebih di sebahagian kawasan Timur Tengah dan untuk kadar tertentu untuk kawasan Asia Selatan. Tanpa mengecilkan peran perguruan tinggi yang lain, patut dicatat bahwa jika tanpa adanya jaringan Perguruan Tinggi Agama Islam di tanah air, yang sekarang jumlahnya 55 PTA, yang terdiri dari 11 Universitas Islam Negeri (UIN), 26 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan 18 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) [PTKIN], belum lagi 569 perguruan tinggi swasta (PTKIS) – baik yang ada di bawah persyarikatan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama mupun lainnya - yang terdiri dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Institut Agama Islam (IAI), dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum.[17] Tanpa jasa perguruan tinggi agama negeri dan swasta, yang umumnya berpola “moderat”, kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada bangsa ini dan bagaimana bangsa ini ke depan, dari Sabang sampai Merauke, dapat menjaga kestabilan sosial-politik-agama dan masih bisa tegak berdiri kokoh seperti sekarang ini. [18]
Di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia, tidak atau belum semuanya dapat menerima dengan sepenuh hati model tata kelola negara dan pemerintahan dengan sistem negara-bangsa (nation state) seperti yang dilakukan di Indonesia, yaitu tata kelola negara-bangsa yang bertumpu dan berbasis pada Konstitusi (Undang-undang Dasar 45), Pancasila, Kebinneka Tunggal Ika an, Demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Salah satu poin penting dalam undang-undang dasar dalam negara-bangsa adalah demokrasi, yaitu dilaksanakannya pemilihan umum secara jujur dan adil untuk memilih wakil rakyat lewat pemilu (pemilihan umum) (legislatif) dan memilih calon presiden (eksekutif) lewat pilpres (pemilihan presiden). Tidak banyak negara berpenduduk Muslim terbesar, sebutlah sebagai contoh Pakistan dan Mesir, berhasil dengan baik dalam menjalankan perintah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menyelenggarakan pemilu dan pilpres. Dalam menjalankan pemilihan umum, di Pakistan, misalnya, hampir pasti disertai kerusuhan yang berakibat jatuhnya korban. Korban bisa dari antar para peserta/kontestan pemilu dan pilpres atau bahkan diantara para kandidat calon pemimpin negara (presiden; perdana menteri) itu sendiri.
Di Mesir juga begitu. Tempo hari, ketika presiden Husni Mubarak terlalu lama memerintah (30 tahun), - dan hal ini sesungguhnya tidak sesuai dengan konstitusi -, maka ada gerakan rakyat (people power) untuk menurunkannya dari kursi kepresidenan. Mirip-mirip apa yang terjadi di tanah air tahun 1998. Mencari penggantinya, juga tidak mudah. Banyak jatuh korban disana. Setelah terpilih presiden baru, ternyata sebagian masyarakat dan pendukung presiden terpilih juga tidak dapat memahami dan menjalankan Konstitusi dengan baik. Kemudian, dijatuhkan lagi. Apalagi di Afganistan, Suria, Iraq dan berbagai tempat yang lain seperti Libia, situasinya hingga kini belum kondusif. Arab Spring belum berhasil menyelesaikan pekerjaaan rumah sebagai negara-bangsa dengan menegakkan konstitusi dan demokrasi sebagai salah satu pilar pentingnya. Menurut catat Persyarikatan Bangsa-bangsa (PBB), krisis politik di Suria sejak tahun 2011 memakan korban tidak kurang dari 191.000 orang, bahkan terus bertambah dari dari ke hari. Ketidak-berhasilan mengelola negara-bangsa ini dipertajam dan diperparah dengan dideklarasikannya Islamic State of Iraq and Syuria (ISIS) atau Negara Islam Iraq dan Suria (NIIS) pada tahun 2013. Berita yang menghangat di penghujung Ramadlan dan hari raya Idul Fitr 1435/2014 sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kekerasan di Suria makin menjadi-menjadi.
Sumbangan intelektual Muslim Indonesia untuk kebangsaan dan keindonesiaan.
Dengan perbandingan seperti itu, lalu kita semua teringat kembali tentang apa yang diserukan pemikir Muslim Indonesia yang lain tentang pentingnya bersikap toleran dan non-diskriminatif terhadap berbagai perbedaan paham, kepercayaan, agama, sekte, suku, ras, gender, kelas dan begitu seterusnya. Seruan ini dikumandangkan secara terus menerus, tanpa kenal lelah, dan bukannya tanpa risiko sumpah serapah dari golongan yang tidak sepaham, sehingga dapat mengantarkan bangsa Indonesia dapat menjalankan konstitusi bernegara 5 tahunan, yaitu memilih calon kepala negara/presiden dengan baik, sukses, tanpa aral yang melintang. Meskipun dalam proses menarik suara pemilih, diantara sebahagian para juru kampanye, da’i, simpatisan dan relawan memanfaatkan isu agama, keyakinan, dan ras (black campaign), namun pada level grassroots tidak sampai terjadi gesekan dan pertikaian yang berarti. Tanpa mengecilkan peran umat beragama lain, peran umat Islam yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia menjadi tulang punggung keberhasilan pemahaman ide “negara-bangsa” dan “demokrasi” seperti yang termaktub dalam undang-undang dasar Republik Indonesia. Mereka tidak mudah terkotak-kotak dan tercabik-cabik oleh isu perbedaan agama, keyakinan, ras, suku dan kelas meskipun godaan, tarikan, hasutan, ajakan, himbauan dan kadang dengan intimidasi dan ancaman selalu ada di setiap saat dan kesempatan.
Setidaknya ada 3 hal penting yang telah dikondisikan oleh para cerdik-cendekiawan Muslim Indonesia dan patut dicatat sebagai legacy mereka dalam upaya menegakkan konstitusi dalam negara-bangsa moderen dan merawat kelangsungan kehidupan demokrasi, dan kebijakan negara yang non-diskriminatif di tanah air. Sebuah legacy yang kemudian disebarluaskan oleh banyak orang, perguruan tinggi agama, perguruan tinggi umum, lembaga swadaya masyarakat, klub-klub diskusi dan pegiat sosial yang lain.
Pertama, konvergensi keimanan agama (distinctive values) dan kemaslahatan berbangsa-bernegara (shared values).
Umat Islam Indonesia – begitu juga umat beragama yang lain[19] -telah dapat secara matang, dewasa, cerdas, otonom, mampu secara mandiri mempertimbangkan, mendialogkan, memperjumpakan secara kritis-proporsional menuju titik konvergensi antara keimanan, kepercayaan dan ritual keagamaan Islam (distinctive values) di satu sisi dan kemaslahatan dan kepentingan bersama (shared values), di sisi lain, untuk tercapainya persatuan-kebangsaan dan perdamaian dalam format negara-bangsa. Dalam pemilihan presiden tahun 2014. tidak kurang dari 133.574.277 suara sah, [(Capres No. 1: 62.576.444/46,85%) dan Capres No.2: 70.997.833/53,15%)] yang masuk ke bilik suara. Mereka secara berdaulat menggunakan hak pilih sesuai panggilan hati dan pilihan rasional masing-masing. Mereka tidak tergoda atau terpancing oleh isu-isu negatif yang memanfaatkan sentimen ras, suku, etnis dan keagamaan untuk memilih calon presiden dan wakilnya saat itu. Kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di tanah air akan selalu diuji daya tahan nya setiap 5 tahun sekali, dalam pemilu dan pilpres, belum lagi berpuluh pilkada, pilgub, belum lagi pilkades di tanah air.
Dalam poin ini, masyarakat Muslim Indonesia mempunyai keunggulan kualitatif dan komparatif dibanding dengan bangsa-bangsa lain yang berpenduduk mayoritas Muslim di dunia. Bangsa-bangsa lain tidak atau belum mampu melakukan dialog positif-konstruktif antara keimanan agama, kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang dilakukan dan dialami oleh bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa lain di dunia masih mengedepankan yang satu diatas lain, bahkan tidak jarang yang membenturkannya. Bangsa Indonesia, dapat mendialogkan dan menggunakan pilihan otonom-rasionalnya dalam menentukan calon pemimpin bangsanya, tanpa terpengaruh oleh black campaign yang mendahului dan menyertainya sebelum masuk ke bilik suara.
Tingkat kualitas ke(ber)adaban dan kemartabatan umat beragama dalam bingkai berbangsa dan bernegara – sebutlah berkeindonesiaan - sangat ditentukan bagaimana corak hubungan antara “keimanan dalam agama” (faith) dan “kebhinnekaan kehidupan sosial dalam bangsa-negara” (reason). Hubungan antara keduanya bercorak konflik, independen, dialog atau integrasi kah? Muslim Indonesia dapat mendialogkan, bahkan mengintegrasikannya antara Agama (faith) dan Negara (reason) secara berimbang - proporsional. Perjumpaan dan dialog, hiwar antara keduanya yang gagal mencapai titik puncak kulminasi konvergensi akan berakibat pada bukannya kebenaran dan kesejahteraan bersama yang akan diperoleh tetapi malah sebaliknya, defisit kebenaran dan kesengsaraan yang akan diperoleh.
Kedua, Kebinnekaan, inklusivitas dan demokrasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari teori maslahah (maqasid al-syari’ah).
Indonesia adalah negara dalam bentuk kepulauan (archipelago). Tidak kurang dari 17.500 pulau besar dan kecil dan hampir 75% merupakan laut, dengan garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km – salah satu yang terpanjang di dunia. Belum lagi fakta bahwa Nusantara memiliki sekitar 300 suku dengan sekitar 300 bahasa daerah (sekitar 580 bila termasuk dialek), tanpa pertumpahan darah.[20] Sedari dulu, sebelum Indonesia merdeka dan menjadi negara-bangsa pada tahun 1945, masyarakat di nusantara sudah sangat bercorak bhinneka. Kemajemukan dan kepelbagaian adalah rajutan tenun sosial-budaya-ekologi masyarakat nusantara sejak dahulu kala. Karena kompleksitas kebhinnekaan/kemajemukan alam nusantara seperti itulah maka founding fathers negara Republik Indonesia era modern akhirnya memilih sistem tata kelola pemerintahan dalam bentuk negara-bangsa. Selain suku, etnis, ras, bahasa, agama dan kepercayaan yang beraneka ragam, juga jika dilihat dari geograpi, territorial bahkan dari segi waktu pun (Timur, Tengah, Barat) beragam.
Nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut. Penghuni daerah kepulauan di wilayah Nusantara. Cara berpikir dan mentalitas pelaut yang hidup di kepulauan memang berbeda dari cara berpikir dan mentalitas manusia benua-darat, kontinental. Pelaut di kawasan kepulauan yang singgah di suatu pulau, karena cuaca yang tidak selalu dapat diduga, biasa tertahan sehari, seminggu, atau lebih. Maka lebih baik berdamai dengan penduduk setempat daripada memusuhinya. Begitu pula penduduk suatu pulau di kawasan kepulauan lebih baik berdamai dengan pendatang, sebab siapa tahu suatu waktu mereka akan terdampar di pulau lain. Artinya, manusia Nusantara dari dulunya, dari prasejarahnya, memang suka damai, memiliki sikap keterbukaan, tidak suka konflik, siap menerima kehadiran orang asing, termasuk adat istiadat dan agama yang dibawanya. Mereka tidak pernah membayangkan akan dapat membangun “tembok Cina” atau “tembok Berlin” ketika terjadi konflik ideologi sebagaimana rekannya yang tinggal di benua-darat, continental. [21]
Ingatan kolektif tentang kebhinnekaan, kemajemukan, (pluralitas; diversitas) dan kedamaian dalam berbagai hal ini sangat kuat melekat dan tertanam kuat dalam alam bawah sadar masyarakat suku-suku, etnis, ras dan agama di Indonesia, agama apapun yang dianutnya. Ingatan kolektif alam bawah sadar tentang kebinnekaan dan kemajemukan ini menjadi kekuatan yang luar biasa dahsyatnya untuk membentuk sikap toleran, inklusif, open minded, terbuka, sehingga mudah menuntun untuk menyelesaikan masalah yang rumit dan kompleks secara sosial-keagamaan dan sosial-kebangsaan. Nurcholish Madjid menyebutnya sebagai fitrah majbulah, fitrah yang tertanam kokoh dalam diri manusia, yaitu hati nurani. Kekuatan alam bawah sadar yang terpatri kuat dalam hati nurani tentang kepelbagaian dan inklusivitas tersebut, pada saat yang diperlukan, berubah menjadi energi spiritual yang positif, yang mampu meredam benih-benih perpecahan yang sewaktu-waktu muncul ke permukaan.
Modal sosial-kultural yang menjelma menjadi moralitas politik ini menjadi bahan dasar sosial bangsa Indonesia yang memberi kekuatan imunitas dari tarikan-tarikan egoisme kelompok (ta’assubiyyah; mazhabiyyah, hizbiyyah, ta’ifiyyah). Kekuatan dan modal kultural dan modal sosial ini dalam perjalanannya dipadukan dengan pemahaman dan pengembangan pemikiran Islam Indonesia yang khas dalam menafsirkan ayat al-Qur’an, 18 ayat dalam surat al- Hujurat, khususnya ayat 49:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoarang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Pemahaman doktrin aqidah Tauhid Islam melalui tafsir sosial-kultural keagamaan yang bercorak al-hanifah al-samha’ (toleran), pluralis dan inklusif menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengembangan teori maslahah dan maqasid syari’ah dalam kajian usul al-fiqh kontemporer[22]. Pengembangan teori maslalah dalam usul al-fiqh ini mendapat momentum yang tepat untuk diaplikasikan dan diterapkan di tanah air, dalam format negara bangsa yang berasaskan Pancasila. Inilah yang mungkin disebut oleh Marshall Hodgson sebagai proses Islamicate yang unik dan sangat intricate dan kompleks di kepulauan nusantara, yang kemudian menjelma menjadi Republik Indonesia (1945), jauh setelah disepakatinya Sumpah Pemuda, tahun 1928. Tafsir lain yang bercorak konservatif, fundamentalistik (tidak sensitif terhadap proses sejarah dan budaya yang begitu mendalam dan mendasar dan berkembang sesuai ide-ide kemajuan), primordialistik dan sektarianistik, berorientasi masa lalu, tidak kreatif-inovatif, tidak akan mendapat simpati apalagi dukungan dari masyarakat luas di Indonesia.
Belum tuntas benar persoalan ini, karena Indonesia yang wilayah territorialnya sangat luas, juga tidak dapat terlepas begitu saja dari tarikan-tarikan konservatisme dan fundamentalisme keagamaan baik yang bersumber dari dalam negeri dan lebih-lebih yang datang dari luar negeri. Tarikan dan godaan itu tidak hanya datang dari luar negeri, di dalam negeri pun banyak hal yang dapat menjadi sumber potensial untuk hidup berkembangnya tafsir keagamaan eksklusif-fundamentalistik, bahkan sektarianistik selagi hak-hak warga negara (Rights), pengakuan yang tulus terhadap eksistensi masing-masing pribadi dan kelompok (Recognitions) dan keadilan dan pendistribusian ekonomi (Redistributions) dalam administrasi kepemerintahan negara-bangsa tidak dapat tersampaikan kepada masyarakat secara baik.[23] Artinya, sila ke lima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia adalah agenda besar yang tidak dapat dinomorduakan, apalagi dilupakan oleh siapapun rejim pemerintah yang memimpin negeri ini dari satu masa pemilu ke masa pemilu yang lain. Begitu pemerintah gagal menjalankan dan memenuhi tuntutan amanah Konstitusi dan Pancasila ini, maka tarikan konservatisme dan fundamentalisme baik ke arah kiri maupun ke kanan akan selalu muncul ke permukaaan.
Ketiga, kohesivitas sosial (fitrah majbulah) sebagai modal sosial dan kultural bangsa Indonesia.
Sejak lama para ahli sosiologi agama berpendapat bahwa salah satu fungsi sosial dari agama di tengah masyarakat penganutnya adalah untuk menjaga kohesi dan kesatuan sosial. Ketika teori itu disusun, mungkin yang dibayangkan pencetusnya (Emile Durkheim) adalah kohesi atau kesatuan sosial yang hanya terbatas dalam lingkup intern (lingkaran dalam) umat beragama tertentu itu sendiri. Dalam masyarakat Muslim Indonesia, paska kemerdekaan Republik Indonesia, teori kohesi sosial tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan, kerukunan, perdamaian, soliditas dan solidaritas di lingkungan intern penganut agama tertentu saja, tetapi lebih dari itu. Ia telah diperluas maknanya menjadi Persatuan Indonesia. Disini, sekali lagi, untuk kasus Indonesia, keimanan dalam keagamaan berjumpa, berdialektika dan menyatu dengan ide kebangsaan. Artinya, solidaritas keagamaan yang seringkali bercorak sektarian-primordialistik (ta’ifiyyah; hizbiyyah) berubah, bermetamorfosis menjadi solidaritas kebangsaan-kemanusiaan (al-wataniyyah; al-insaniyyah) Lagi-lagi, ini adalah hal unik dalam pengalaman keagamaan dan kebangsaan masyarakat Indonesia. Namun, hal ini sulit tercapai, jika saja sebelumnya tidak dilapisi modal sosial dan modal kultural yang telah terpatri kuat, terajut rapi, mendarah-mendaging dalam struktur dan alam pikir bawah sadar masyarakat Indonesia, apapun suku, ras, etnis, bahasa dan agama yang dipeluknya.
Pertemuan dan perjumpaan antar beranekaragamnya etnis, ras, suku, bahasa, agama dan kepercayaan di tanah air itulah yang telah menjadi kekuatan alam bawah sadar dan menjiwai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pertemuan dan perjumpaan yang positif-konstruktif itulah yang berjasa besar mengantarkan rakyat Indonesia dapat keluar dari kemelut yang amat kompleks sebelum, ditengah-tengah dan sesudah pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2014.. Pada titik ini, terngiang kembali diktum “Islam Yes, Partai Islam, No?”. Semuanya ini adalah karunia, anugerah dan rahmat Allah yang tiada bandingannya, yang patut dishukuri bersama.
Tatanan masyarakat grassroots Indonesia mirip-mirip yang dilukiskan oleh al-Qur’an, dalam surat Ali ‘Imran, 159 sebagai berikut :
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.[24]
Tantangan yang dihadapi.
71 tahun pasca proklamasi Indonesia banyak peristiwa terjadi. Geopolitik nasional dan internasional terus berubah dan bergolak secara dinamis dan itu berpengaruh besar pada ketahanan mental beragama dan berpolitik rakyat dan bangsa Indonesia. Menjelang dan sesudah terbentuknya orde Reformasi (1998) terjadi serentetan konflik antar umat Kristiani dan Muslim di Ambon, lalu merembet ke Poso; kemudian disusul dengan pengrusakan dan pengeboman beberapa tempat ibadah dan konflik antar suku dan ras seperti di wilayah Kalimantan Barat dan wilayah Papua. Tahun 2001, terjadi peristiwa penghancuran dan runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) New York, disusul tahun 2002 bom Bali di Indonesia dan peristiwa peledakan bom di berbagai negara yang lain, maka sekarang pun dunia masih dibayang-bayangi oleh gerakan al-Qaeda dan belakangan disusul dengan deklarasi pembentukan Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) yang sebagian pendukungnya adalah juga sebahagian kecil warga Indonesia. Masih segar dalam ingatan kita peristiwa Tolikara di Papua dan Singkili di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2015.
Semua peristiwa itu menandakan bahwa pemikiran Islam Indonesia yang digagas oleh banyak aktor seperti kerja-kerja intelektual yang lain, jauh dari final dan belum selesai. Masih banyak rintangan, halangan dan batu sandung ujian yang terus menghadang di setiap waktu dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara dalam republik Indonesia. Jika dipetakan wilayah pemikiran dan praksisnya di lapangan menjadi tiga lapis, yaitu, pertama, level discourse (al-khitab) atau wacana; kedua, level normatif-regulatif, dan ketiga adalah level aplikasi-implementasi dalam kehidupan masyarakat riil di lapangan, maka para cerdik-cendekia Muslim dan teman-teman yang lain sudah berhasil pada level mengangkat isu pluralitas, diversitas, inklusivitas dan toleransi (al-hanifa al-samha’) dan multikulturalitas dalam kehidupan beragama dan berbangsa-bernegara pada level discourse publik. Sebuah sumbangan intelektual yang luar biasa pentingnya karena tidak banyak bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dapat menerima discourse tersebut. Berapa banyak buku yang dilarang masuk ke suatu negara tertentu – jangankan sampai di baca – karena membahas persoalan pluralitas, diversitas, inklusivitas atau al-ta’addudiyyah ini.
Tidak semua level dan lapis tersebut harus diselesaikan oleh barisan para cerdik-cendekia tersebut. Pada level normatif-regulatif masih banyak batu sandung di masyarakat luas, di berbagai kementrian, baik kementrian agama, kementrian dalam negeri dan kementrian hukum dan HAM maupun kementrian lainnya. Kalau tidak salah, undang-undang No.1, tentang PNPS tahun 1965, yang terkait dengan persoalan Penodaan Agama belum ada yang berani menyentuh, bahkan Mahkamah Konstitusi sekalipun. Lebih-lebih pada level aplikasi dan implementasi. The Social Hostility Index di tanah air, menurut laporan Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life “Rising Restriction of Religion” (2011) menempati rangking cukup tinggi. Hal ini tidak sinkron dengan beberapa aturan yang dikeluarkan pemerintah (The Government Restriction Index). Ketika seorang menjadi terpilih menjadi pimpinan publik, pimpinan organisasi agama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, gubernur, bupati, kepala desa dan begitu seterusnya maka keadaannya sangat situasional sekali. Ada yang berhasil dan ada yang tidak, tergantung pada corak kedalaman, kematangan dan penguasaan religious, social, cultural dan political literacy nya, terlebih pada pemahaman dan penguasaan ketiga lapis pemikiran yang saling terkait tersebut.
Apakah ini semua dapat disebut sebagai paradox dari pluralitas? Saya kira tidak. Karena tiga lapis penyelesaian permasalahan keagamaan dan kebangsaan bukan semacam kerja teknis-teknologis yang bersifat once for all, tetapi ini adalah kerja humanistik yang memerlukan kerja yang lebih detil dan berkesinambungan, lebih dari itu kerja kerelawanan (altruism; volunterism) harus berjalan kompak dan terus menerus berkesinambungan diperbaiki (continous improvement). Masih banyak pekerjaaan rumah yang ditinggalkan oleh para cerdik cendekia dan generasinya dan karenanya para penerus mereka sekarang jangan puas diri karena tantangan pada level normatif-regulatif dan aplikasi-implementatif masih menunggu di depan mata. Bagaimana kebijakan publik (public policy) pada wilayah pendidikan, pengelolaan anggaran, rekruitmen pegawai, managemen perumahan, tata ruang, termasuk pendirian rumah ibadah dan begitu seterusnya dilakukan? Dan wilayah ini jauh lebih sulit dan kompleks. Generasi berikutnya, generasi penerus harus dapat meneruskan perjoangan pendahulu dalam menyumbangkan pengembangan pemikiran Islam Indonesia tersebut.
Jangan kita kehilangan optimisme melihat perjalanan bangsa ke depan. Manusia Indonesia adalah manusia dan bangsa yang memiliki modal kultural dan sosial yang kuat. Modal sosial-kultural itulah yang sementara ini telah dapat mengantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara bermartabat dan beradab dalam bernegara dan berbangsa jika ukuran sementaranya adalah suksesnya penyelenggaraan pemilihan presiden tempo hari (2014). Masih banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Bagaimana membangun daya saing bangsa memasuki era perdagangan bebas dunia, perdagangan bebas masyarakat Asia tahun 2015, mengembangkan dan memproduksi ilmu pengetahuan, a greater inter-faith interaction dalam dunia yang semakin kosmopolit, masih tingginya angka kemiskinan, kekerasan sosial, kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak dan wanita, banjir minuman keras, narkoba dan sejenisnya, teknologi IT yang membawa residu pornografi, yang belum terantisipasi sama sekali ketika agama masih dijelaskan dengan cara face to face - bermuwajahah seperti era dahulu, syi’ar kebencian dan paham keagamaan yang eksklusif, kekerasan sosial bermotif dan berdalih perbedaan agama, madzhab, aliran, penafsiran teks-teks keagamaan secara subjektif, konservatisme dan fundamentalisme agama, kebencian dan kekerasan atas nama agama, ideologi takfir–takfiriyyah, meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapis bawah/kecil, rekonsiliasi sosial, politik dan budaya, kerukunan intern umat Islam, kerukunan antar umat beragama, membangun media sosial yang literate tentang isu-isu pluralitas agama, sensitivitas terhadap sains, sensitivitas terhadap difable, pemberantasan dan pencegahan tindak korupsi dan masih banyak yang lain lagi. Diatas semua itu, bagaimana road map bangsa Indonesia untuk mencapai sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan oleh Persyarikatan Bangsa-bangsa.
Masih terbuka harapan baru untuk kesejahteraan, kesatuan dan persatuan Indonesia. Apa yang biasa disebut oleh media sebagai rekonsiliasi sosial perlu dimulai dari para elit dan pimpinan. Jangan sampai rakyat Indonesia pada level grassroots lebih dewasa dari pada kaum elitnya dalam mencerna, memediasi, menghindari dan menyelesaikan perbedaan. Maka para elit lah – dengan berbagai kepentingannya - yang perlu mengedepankan dan menjalin tali silaturrahim ideologis agar masyarakat Indonesia tetap dapat mempertahankan persatuan Indonesia, mengkonsentrasikan energi mental, sosial dan spiritual mereka untuk pembangunan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia yang berkemajuan dan mendukung perdamaian dunia. Wallahu a’lam bi al-sawab.
BIBLIOGRAPI
Abu-Rabi’, Ibrahim M., The Contemporary Arab Reader on Political Islam, London and New York: Pluto Press, 2010.
el-Ansary, Waleed dan David K. Linnan, Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of “A Common Word”, New York, Palgrave Macmillan, 2010.
Auda, Jasser, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
Bagir, Zaenal Abidin, dkk., Pluralisme Kewargaaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Yogyakarta, CRCS Universitas Gadjah Mada dan Penerbit Mizan, 2011.
Hodgson, Marshall G.S., The Venture of Islam: Conscience and History in World Civilization, Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1974.
al-Jabiri, Muhammad Abid, al-Turats wa al-Hadatsah: Dirasat wa Munaqasat, Marokko: Dar al-Baidha’, 1991.
Kersten, Carool, Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values, London, C. Hurst and Co. Ltd., 2015.
Kusuma, Mirza Tirta (Ed.), Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik, dan Ideologi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Islam, Jakarta: BulanBintang, 1984.
--------------, Islam: Doktrin dan Peradaban. Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan, Jakarta: Paramadina, 1992.
--------------, Islam: Agama Peradaban. Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.
-------------, Khazanah Intelektual Islam, Jakarta: BulanBintang, 1984.
Markham, Ian and Ibrahim M. Abu Rabi’ (Eds.), 11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences, Oxford: Oneworld Publications, 2002.
Meijer, Roel (Ed.), Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, London: Hurst & Company, 2009.
Saeed, Abdullah, Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach, London and New York: Routledge, 2006.
Safi, Omid (Ed.), Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism, Oxford: Oneworld Publications, 2005.
Shahrur, Muhammad, Nahw Ushulin Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy: Fiqh al-Mar’ah (al-Wasiyyah-al-Irts-al-Qawwamah-al-Ta’addudiyyah-al-Libas), Damaskus, Suria: al-Ahali li al-tiba’ah wa al-nasyr wa al-tauzi’, 2000.
Sumartana, Th., Soal-Soal Teologis dalam Pertemuan Antar Agama, Yogyakarta, Interfidei, 2015.
Tabrani, Primadi, Belajar dari Sejarah dan Lingkungan, Bandung, Penerbit ITB, 2011.
*Tulisan ini pengembangan dari tulisan yang pernah disampaikan di Paramadina.
[1]Muhammad Shahrur, Nahw Ushulin Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy: Fiqh al-Mar’ah (al-Wasiyyah-al-Irth-al-Qawwamah-al-Ta’addudiyyah-al-Libas), Damaskus, Suria: al-Ahali li al-tiba’ah wa al-nasyr wa al-tauzi’, 2000, h. 116.
[2]Saya merujuk pada realitas peta baru dunia Islam pada paroh kedua abad ke 20, dimana migran Muslim terus tumbuh dan berkembang di negara-negara Barat. Diantara mereka adalah para intelektual dan scholar Muslim yang menulis buku-buku literatur keagamaan Islam pada level akademik dengan perspektif baru, yang berbeda dari perspektif pemikiran Islam yang digunakan sebelumnya. Buku-buku seperti Omit Safi (Ed.), Progressive Muslims, atau Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach, misalnya, sekarang dan akan datang akan mewarnai dinamika pemikiran Islam dimanapun berada.
[4]Dalam memberi Kata Pengantar buku Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of “A Common Word”, h. 2-4. Waleed El-Ansary dan David K. Linnan menyebut ada 6 zona wilayah Islam sekarang, yaitu 1. Zona Arab. Disatukan secara bahasa tetapi beranekaragam secara etnis. Di zona ini ada sekitar 250 juta Muslim. 80 % dari Muslim di dunia tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa harian.2. Zona Persia (Iran, Afganistan dan Tajikistan). Ada 110 juta Muslim disini. 3. Zona Afrika [Black Africa], Ghana, Mali. Zona sub-Sahara ini dihuni tidak kurang dari 200 juta Muslim. 4. Zona Turki, Bahasa Turki dominan di wilayah ini. Wilayah Asia Tengah masuk di zona ini. Membentang dari wilayah Balkan sampai ke Siberia. Ada sekitar 170 juta Muslim. 5. Zona India (Asia Selatan). Hampir 500 juta Muslim. Terdiri dari Pakistan, Bangladesh, India, Nepal, dan Sri Langka. Bahasanya macam-macam, Sindhi, Gujrati, Punjabi, Bengali, Urdu. Bahasa Persi pernah digunakan sebagai bahasa intelektual dan sastra di wulayah ini. 6. Zona Melayu di wilayah Asia Tenggara. (Malaisia, Indonesia, Brunei dan minoritas Muslim di Thailand, Pilipina, Kambodia dan Vietnam. Tidak kurang dari 240 juta Muslim disini. Di luar 6 zona ini, masih ada wilayah lain seperti di Cina, sekitar 100 juta Muslim, masyarakat minoritas Muslim di Eropa dan Amerika.
[5]Sudah lama kebutuhan ini dirasakan oleh umat Islam Indonesia. Berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tahun 1951 adalah bagian sejarah penting pengembangan pendidikan keagamaan Islam di tanah air. Hal ini diperkuat dengan transformasi kelembagaan dan keilmuan dari IAIN ke Universitas Islam Negeri (UIN) pada tahun 2000an. Sekarang dapat dijumpai di IAIN, apalagi di UIN faklutas yang disebut dengan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (dulunya hanya disebut fakultas Ushuluddin), Fakultas Adab dan Humaniora (dulunya disebut fakultas Adab), Dakwah dan Komunikasi (dulunya disebut fakultas Dakwah) dan begitu seterusnya.
[6]Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Vol. 1,Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
[8]Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin dan Peradaban. Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992. Bahkan pada tahun 1995, buku cak Nur yang lain, secara eksplisit menyebut ‘sejarah’. Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, buku-buku seperti ini bukannya tidak ada. Muhammad Abid al-Jabiri pernah menulis buku al-Turats wa al-Hadastah: Dirasat wa Munaqasat, Marokko: Dar al-Baidha’, 1991.
[10]al-Hanifa al-samha diartikan sebagai “the true and tolerant religion”. Lihat Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English), Wiesbaden, Otto Harrassowittz, 1976, h. 500. Juga biasa disebut hanifiyyatu al-samhah.
[11]Roel Meijer, “Introduction”, dalam Roel Meijer (Ed.), Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, London: Hurst & Company, 2009, h. 9-13.
[12]Tidak mudah menjelaskan bagaimana geopolitik di negara-negara di Timur Tengah. Ibrahim M. Abu Rabi’, seorang Palestina, yang lama tinggal dan mengajar perguruan tinggi di Barat menulis kata pengantar buku yang ia edit, yang cukup mambantu menjelaskan kerumitan tersebut. Ibrahim M. Abu-Rabi’ (Ed.), The Contemporary Arab Reader on Political Islam, London dan New York: Pluto Press, 2010.
[13]Ketika tulisan ini semula disusun, saya mendengarkan siaran berita dan membaca running text MetroTV , tanggal 22 -23-24 Agustus 2014, yang memberitakan adanya ancaman pengrusakan candi Borobudur, karena dianggap sebagai syirk dan dianggap sebagai penghambur-hamburan uang untuk pemeliharaan cagar budaya tersebut. Berita seperti ini juga pernah muncul sekitar tahun akhir 1970an dan saya kira akan berlanjut kapanpun karena ideologi tersebut ditanamkan dan disebarluaskan lewat buku, bulletin, selebaran-selebaran, media sosial, media elektronik dan media apapun yang dimiliki.
[14]Uraian tentang hubungan antara agama, politik dan ideologi, khususnya yang terkait dengan keterkaitan dan ketidak kesinambungan antara pemahaman bid’ah dan syirk dan sensivitas sejarah dan budaya dapat dibaca dalam Mirza Tirta Kusuma, “Ketika Makkah menjadi Las Vegas” dalam Mirza Tirta Kusuma (Ed.), Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik dan Ideologi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, h.1-69.
[15]Sejak tahun 2000 an terbitlah buku-buku serial yang bertujuan untuk “memperbaiki pemahaman” orang Muslim tentang agamanya (Silsilatu tashhih al-mafahim). Antara lain dapat dijumpai buku-buku serial kecil seperti (1) Taslith al-adhwa’ ‘ala ma waqa’a fi al-jihad min al-akhta’; (2) al-Nush wa al-tabyiin fii tashhih mafahim al-muhtasibin; (3) Mubadarah waqf al-‘Unf: ru’yah waqi’iyyah .. wa nadzrah syar’iyyah; (4) Hurmah al-ghuluw fii al-diin wa takfir al-Muslimin. Keempat serial buku tersebut diterbitkan oleh Maktabah al-Turats al-Islamiy, al-Qahirah, 2002.
[16]Ibrahim M. Abu Rabi’, “A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History”, dalam Ian Markham and Ibrahim M. Abu Rabi’, 11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences, Oxford: Oneworld, Publications, 2002, h. 33-34. Cetak hitam dari saya. Dalam halaman 36 bahkan disebutkan bahwa “ The discipline of the sociology of religion is looked upon as a bid’ah, or innovation, that does not convey the real essence of Islam”.
[17]Dapat ditelusuri Buku Statistik Pendidikan Islam, Jakarta, Bagian Perencanaan Sekretariat Pendidikan nIslam, 2015. Juga pada website diktis.kemenag.go.id.
[18]Tidak banyak peneliti dari dalam negeri maupun luar yang meneliti peran perguruan tinggi agama (Islam) dalam percaturan kebangsaaan di tanah air. Dari salah satu yang sedikit itu dapat ditelaah buku Carool Kersten, Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values,London, C. Hurst and Co. Ltd., 2015, h. 263-273.
[19]Umat beragama lai n juga bukannya passif dalam menghadapi persoalan keagamaan dan kebangsaan. Salah satu pegiat dialog antar agama di lingkungan Kristiani yang sampai sekarang masih aktif adalah Interfidei (Inter Faith Dialogue) di Yogyakarta. Tahun 2016, Interfidei berulang tahun ke 25. Betapa sulitnya menghadapi pluralitas di lingkungan umat Kristiani tergambar dalam Skripsi yang ditulis Th. Sumartana tahun 1971. Skripsi ini telah diterbitkan awal tahun 2015 oleh Interfidei berjudul Soal-soal Teologis dalam Pertemuan Antar Agama, Yogyakarta, Interfedie, 2015.
[22]Jasser Auda, Maqasid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008, h. 5-9; 21-25.